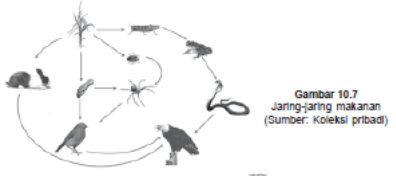secara terus menerus yang ditandai dengan adanya aliran energi,
daur materi, dan produktivitas ekosistem.
Perhatikan Gambar 10.4! Sumber energi dari suatu ekosistem berasal
dari cahaya matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tumbuh-
tumbuhan sebagai produsen membutuhkan cahaya tersebut untuk
melakukan proses fotosintesis, dimana sebagian energi tersebut berpindah
kepada konsumen I dan dalam bentuk makanan, selanjutnya berpindah
lagi kepada konsumen II dan III.
Jika produsen dan konsumen mati, akan menjadi sampah organik.
Sampah tersebut mengalami pembusukan dari hasil penguraian mikroba
tanah sehingga menjadi humus, sebagian lagi terurai menjadi gas atau mineral.
Sampai di sini, materi yang berupa gas atau mineral dimanfaatkan
lagi oleh tumbuhan (produsen).
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aliran energi berbeda dengan
aliran materi. Aliran materi bersifat siklus, sedangkan aliran energi bersifat
menuju satu arah, yaitu sampai pada tingkat mikroba.
a. Matahari sebagai Sumber Energi
Coba bayangkan, seandainya di planet bumi ini tidak ada matahari!
Bagaimana keadaannya? Dapat dipastikan keadaan bumi gelap gulita
sepanjang masa dan dingin. Matahari mengeluarkan energi panas dan cahaya.
Dengan energi cahaya itu, bumi menjadi terang dan bumi menjadi hangat
karena panasnya. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas ciptaannya ini.
Sinar matahari merupakan foton (energi sinar) yang dipancarkan ke jagad
raya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, tetapi hanya sebagian kecil
saja yang sampai di permukaan bumi, yaitu sekitar 10,5 × 106 kj m-2 th-1. Dari
jumlah pancaran energi sinar matahari itu, sekitar 5 × 106 kj m-2 th-1 atau sekitar
45% yang sampai di bumi, sekitar 40% dipantulkan lagi keluar angkasa oleh
atmosfer bumi, dan hanya sekitar 15% saja yang diserap untuk pemanasan
atmosfer bumi, terutama pada lapisan ozon dan kelembapan udara (uap air).
Dari sekitar 45% sinar matahari yang jatuh di permukaan bumi, sekitar
30% dipantulkan kembali dan memanaskan atmosfer, dan selebihnya sekitar
15% dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi komponen ekosistem
di permukaan bumi. Dengan demikian, keberadaan setiap ekosistem di
permukaan bumi diikat oleh aliran atau arus energi yang berasal dari sinar
matahari yang bersifat satu arah.
b. Aliran Energi
Secara langsung maupun tidak langsung, sumber energi setiap ekosistem
berasal dari sinar matahari yang diubah oleh tumbuhan hijau (autotrof)
menjadi energi kimia dalam bentuk zat-zat organik (makanan) melalui proses
fotosintesis.
Pada proses fotosintesis, bentuk energi diubah dari energi cahaya menjadi
energi kimia dan berpindah ke konsumen I, II, dan III, yang berakhir pada
proses penguraian. Di dalam proses penguraian, energi ini dilepaskan dalam
bentuk panas, kemudian tersebar ke lingkungan dan tidak dapat dimanfaatkan
lagi. Perhatikan lagi Gambar 10.4! Dalam hal ini terjadi jalur makan dan
dimakan, yaitu proses produsen yang dimakan oleh konsumen I, selanjutnya
konsumen I dimakan konsumen II, konsumen II dimakan konsumen III. Peristiwa
ini disebut sebagai rantai makanan.
1) Rantai Makanan
Seperti yang Anda ketahui saling ketergantungan antara produsen dan
konsumen tampak pada peristiwa makan dan dimakan. Energi dalam bentuk
makanan akan berpindah dari organisme tingkat tinggi ke organisme lain
yang tingkatannya lebih rendah melalui rentetan organisme memakan organisme
sebelumnya dan sebagai penyedia bahan makanan bagi organisme
berikutnya yang disebut rantai makanan.
Pada umumnya, tipe rantai makanan
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.
a) Rantai Makanan Perumput
Pada tipe ini, mata rantai makanannya berawal dari tumbuhan, maka
tingkat trofi 1 diduduki oleh tumbuhan hijau (produsen), tingkat trofi 2
diduduki oleh herbivora (konsumen 1), tingkat trofi 3 diduduki oleh karnivora
(konsumen 2), dan seterusnya.
b) Rantai Makanan Detritus
Mata rantai makanan pada tipe ini berawal dari organisme perombak.
Ingat kembali, detritus merupakan hancuran (fragmen) dari bahan-bahan
sudah terurai yang dikonsumsi hewan-hewan kecil seperti rayap, cacing
tanah, tripang, dan sebagainya.
c) Rantai Makanan Parasit
Pada tipe rantai makanan parasit, terdapat organisme lebih kecil yang
memangsa organisme lebih besar.
2) Jaring-Jaring Makanan
Dari uraian komponen biotik di atas, pada tiap-tiap tingkatan konsumen
tampak seolah-olah setiap organisme hanya memakan atau dimakan oleh satu
macam organisme yang lain, tetapi kenyataannya di dalam ekosistem keadaannya
lebih kompleks.
Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena tiap-tiap organisme
dapat memakan dalam satu tingkatan konsumen atau dari tingkatan konsumen
lain di dalam ekosistem yang dikenal dengan rantai makanan dan antara rantairantai
makanan itu saling berhubungan satu dengan lainnya yang dikenal dengan
jaring-jaring makanan seperti terlihat pada Gambar 10.5.
Rangkaian peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem tidak
sesederhana rantai makanan. Seperti tampak pada Gambar 10.5, ternyata
konsumen tidak hanya tergantung pada satu jenis makanan, sebaliknya
satu jenis makanan dapat dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen.
3) Piramida Ekologi
Telah kita ketahui bersama, bahwa komponen-komponen biotik pada
rantai makanan ekosistem menempati tingkatan trofi tertentu, seperti
produsen menempati tingkat trofi pertama, herbivora menempati tingkat trofi
kedua, karnivora menempati tingkat trofi ketiga, dan seterusnya.
Ketika organisme autotrof (produsen) dimakan oleh herbivora (konsumen I),
maka energi yang tersimpan dalam produsen (tumbuhan) berpindah ke tubuh
konsumen I (pemakannya) dan konsumen II akan mendapatkan energi dari memakan
konsumen I, dan seterusnya.
Setiap tingkatan pada rantai makanan itu disebut taraf trofi. Ada
beberapa tingkatan taraf trofi pada rantai makan sebagai berikut.
a) Tingkat taraf trofi 1 : organisme dari golongan produsen (produsen primer)
b) Tingkat taraf trofi 2 : organisme dari golongan herbivora (konsumen primer)
c) Tingkat taraf trofi 3 : organisme dari golongan karnivora (konsumen sekunder)
d) Tingkat taraf trofi 3 : organisme dari golongan karnivora (konsumen predator)
Di dalam rantai makanan tersebut, tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan,
tetapi hanya sebagian yang mengalami perpindahan dari satu organisme
ke organisme lainnya, karena dalam proses transformasi dari organisme
satu ke organisme yang lain ada sebagian energi yang terlepas dan tidak
dapat dimanfaatkan. Misalnya, tumbuhan hijau sebagai produsen menempati
taraf trofi pertama yang hanya memanfaatkan sekitar 1% dari seluruh
energi sinar matahari yang jatuh di permukaan bumi melalui fotosintesis
yang diubah menjadi zat organik.
Jika tumbuhan hijau dimakan
organisme lain (konsumen primer),
maka hanya 10% energi yang berasal
dari tumbuhan hijau dimanfaatkan
oleh organisme itu untuk pertumbuhannya
dan sisanya terdegradasi
dalam bentuk panas terbuang ke atmosfer.
Dengan demikian, energi
yang tersedia untuk tingkat trofi pada
rantai makanan seperti berikut: semakin
tinggi tingkat trofi, semakin
sedikit sehingga membentuk sebuah piramida yang disebut piramida ekologi,
seperti pada Gambar 10.6. Selama keadaan produsen dan konsumenkonsumen
tetap membentuk piramida, maka keseimbangan alam dalam
ekosistem akan terpelihara.
Ada 3 macam-macam piramida ekologi adalah sebagai berikut.
a) Piramida Jumlah
Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam
suatu daerah (areal) tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan
taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam
bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan
jumlah organisme dalam areal tertentu.
Pada piramida jumlah, golongan
organisme yang berada pada tingkatan
lebih tinggi memiliki jumlah organisme
lebih banyak dari tingkatan
organisme di bawahnya. Piramida
tersebut dapat digambarkan seperti
pada gambar di samping.
Pada tingkat trofi I memiliki jumlah
yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofi II dan tingkat trofi II lebih
besar dibandingkan dengan tingkat trofi III.
b) Piramida Berat (Biomassa)
Penggunaan piramida jumlah sering berubah-ubah karena keadaan
lingkungan, untuk itu digunakan piramida berat (biomassa).
Piramida berat (biomassa) merupakan
taksiran berat organisme yang
mewakili setiap taraf trofi dengan
cara tiap-tiap individu ditimbang dan
dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem.
Misalnya biomassa tumbuhan
di ukur berat akar, batang, dan daun
yang menempati areal tertentu. Piramida
biomasa dibuat berdasarkan
berat total populasinya pada suatu waktu.
Satuan yang dipakai adalah berat total organisme dalam satuan berat
(gr/kg) per satuan luas tertentu (m² atau hektar) yang biasanya diukur dalam
berat kering. Untuk mengukur biomassa seluruhnya, dilakukan teknik sampling
(cuplikan) guna memperkirakan seluruhnya.
Penafsiran dalam piramida biomassa memerlukan banyak waktu dan
peralatan dalam melakukan penimbangan individu-individu dan mencatat
jumlahnya. Penggunaan piramida ini tidak memuaskan karena bentuk yang
berubah-ubah. Hal ini tergantung pada iklim dan dalam transfer energi
sebagian akan hilang, yaitu digunakan untuk respirasi atau sebagai panas
yang masuk ke biosfer.
c) Piramida Energi
Piramida energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Piramida ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat memperhitungkan
kecepatan produksi, berat dua species yang sama tidak harus memiliki energi
yang sama, dapat digunakan untuk membandingkan berbagai ekosistem,
adanya masukan energi matahari yang ditambahkan.
Piramida energi ini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam
6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Satuan
energinya dinyatakan dalam kalori per m² per satuan waktu (kal/m2/th).